Dimuat di Indonesia Art News, Senin/2 Juli 2012
http://indonesiaartnews.or.id/bukudetil.php?id=11
POLOS nian ekpresi anak-anak lereng Merapi, walau sebenarnya mereka
geram menyaksikan penambangan pasir yang merusak alam desa Sumber,
Muntilan, Jawa Tengah. Maka, tatkala bocah-bocah tersebut berpapasan
dengan truk-truk penjarah pasir di jalan, tanpa ada yang mengkomando
mereka sontak terdiam. Lantas, apakah anak-anak desa itu kemudian
melempari batu? Ternyata tidak, mereka hanya tak mau mengeluarkan
sepatah kata pun. Tetapi begitu terbebas dari pandangan yang menyiksa
itu, mereka kembali berlarian, bersenda-gurau, dan bersiul gembira.
Begitulah penuturan Romo Vincentius Kirjito Pr selaku "pamong" mereka.
Putra pasangan Kromo Pawiro dan Padinem ini merupakan alumni Seminari
Tinggi Kentungan, Yogyakarta. Ada satu prinsip yang menarik untuk
dicermati. Baginya, media massa bukan sekadar “panggung” untuk
pemberitaan sebagai seorang pesohor.
Dalam konteks ini, sungguh berbeda dengan kecenderungan para elit
politik yang 'hobi" menggelar konferensi pers. Paderi desa kelahiran
Menoreh, 18 November 1953 tersebut memaknai interaksi dengan media
massa tak cukup sekadar menjalin komunikasi antara seorang berjubah
dengan pekerja pers. Kenapa? Karena ini lebih merupakan srawung
(interaksi) antarmanusia yang berkehendak baik.
Pastor Praja (Pr) Keuskupan Agung Semarang (KAS) ini mengaku
terinspirasi dari petuah Romo Y.B. Mangunwijaya. Pada 1987 silam,
tepatnya di Salam, kabupaten Magelang, ada pelatihan terkait
tugas-tugas Imam di dalam masyarakat. Mendiang Romo Mangun berpesan,
“Imam Praja itu punya kesempatan bagus untuk dekat dengan masyarakat,
merasakan denyut nadi, suka-duka masyarakat.
Dalam sistem politik yang semakin menekan masyarakat, seorang Imam
Praja bisa menjadi saluran menyuarakan aspirasinya. Paling tidak bisa
menyalurkan lewat media massa, entah dengan menulis atau
sekurang-kurangnya menjadi narasumber media dalam mencari kebenaran
suatu masalah dalam masyarakat. Karena media massa itu yang memerankan
“wakil rakyat” yang sesungguhnya (halaman v)”.
Buku ini merupakan kompilasi buah pena para insan pers selama 10 tahun
(2001-2011). Isinya menyiratkan betapa komplit dinamika kehidupan
masyarakat di pedesaan. Mulai dari keindahan lingkungan alam sekitar,
kearifan pustaka budaya lokal, hingga keluh-kesah akar rumput dan warta
bahagia dari lereng Merapi. Penulisnya terdiri atas para wartawan media
cetak dan elektronik. Baik dalam skala lokal, nasional, maupun
internasional. Total ada 51 artikel. Terbagi ke dalam 3 sub-bab: Masalah
Ekologi, Pagelaran Budaya, dan Spiritualitas.
“Know Thyself,” sebuah mantra ampuh dari Yunani. Artinya, “Kenalilah
Dirimu.” Menyitir pendapat Anand Krishna. Ternyata, ada 3 macam diri
manusia. Pertama, diri kita menurut orang lain. Kedua, diri menurut
diri kita sendiri. Ketiga, diri kita yang sejati. Lantas, bagaimana
anak-anak Merapi menemukan kembali jati dirinya? Yakni, sebagai bagian
dari kolektivitas wong gunung nan murni itu. Lewat artikel bertajuk,
“Kawruh Sakti untuk Anak-anak Merapi” (halaman 91-94) termaktub
jawabnya.
Alkisah, Anjani berpesan pada Anoman dalam pertunjukan Wahyu
Mangliawan, “Anakku, mulai saat ini jika kamu haus minumlah embun di
pepohonan dan rerumputan, jika kamu lapar makanlah buah dan ubi di
hutan. Itu sama dengan meminum air susu ibumu dan memakan masakan
ibumu. Ketika kamu bersedih karena kesepian, kamu tidak boleh lagi
menangis karena sendiri. Alam ini adalah saudaramu...”
Artinya, kembali ke Bunda alam semesta (back to Mother nature).
Mendekatkan anak-anak dengan lingkungan sekitar dan budaya lokal. Dua
acungan jempol untuk kreatifitas anak-anak lereng Merapi. Terutama
tatkala mereka bermain dhakon. Kenapa? Karena tanpa papan congklak
sekalipun, para "bolang" dusun Gemer, kecamatan Dukun, Muntilan
tersebut masih bisa menikmati keindahan masa kanak-kanak.
Mereka menggambar lingkaran-lingkaran di tanah dan kemudian
mengumpulkan aneka kerikil dari sungai. Menurut Ibu Giyanto yang biasa
mendampingi tunas-tunas muda tersebut, orang tua mereka tak mampu
membelikan mainan ala wong kota seperti Play Station (PS),
pedang-pedangan yang bisa menyala, ataupun televisi berwarna. Kenapa?
Karena 99,9 persen berprofesi sebagai petani (miskin). Keunggulan
dolanan anak ini ialah memfasilitasi interaksi intra dan antar-anak.
Sejak dini mereka dibudayakan bersikap lepas-bebas dan apresiatif
terhadap rekan sepermainan dan lingkungan sekitar.
Marketing Guyup
Buku ini juga memuat artikel ihwal perjumpaan 2 tokoh. Yakni, mengulas
interaksi Hermawan Kertajaya (HK) dan Romo Kirdjito (RK). Pada 18
November 2009, keduanya sempat merayakan pesta ulang tahun di keheningan
alam Merapi. Kebetulan HUT mereka sama. Kenapa kedua pria tersebut
begitu spesial? Karena mereka menyadari ketidakhebatannya. Sehingga
masing-masing tetap mau belajar satu sama lain.
Selama misa Alam, HK—yang dikenal sebagai pakar pemasaran
(marketing)—mengaku merasa kecil dan tiada arti. “Saya betul-betul
merasa kecil dan tidak ada artinya ketika berada di alam. Saya sungguh
merasakan alam tidak membedakan kita. Yang kaya, yang miskin, yang
pinter, yang bodoh, dan lain-lain semua sama di hadapan Alam dan
Tuhan.” (halaman 159).
Pada satu sesi sebelum misa berlangsung, ia diminta mengambil 10
tumbuhan berbeda. HK memang berhasil membawa genap 10 tanaman. Tapi
tidak ada satu pun tumbuhan yang dikenalinya. Walau sekadar rumput
ilalang atau putri malu sekalipun. “Saya mampu mengumpulkan 10 tanaman,
tapi saya tak tahu namanya hehe. Betul-betul nol pengetahuan saya soal
tumbuhan,” ungkapnya di hadapan seluruh peserta misa Alam.
Frietqi Suryaman menyumbangkan sebuah artikel apik. Yakni, ketika
Hermawan Kertajaya hendak memberi kenang-kenangan, berupa piano kepada
masyarakat desa Dukun. Namun RK tidak mau, ia justru menginginkan
disumbang seperangkat alat gamelan untuk masyarakat setempat. Kenapa?
karena kalau piano hanya dimainkan oleh satu orang, sedangkan gamelan
mau tak mau harus dimainkan secara kolektif. Inilah praktik guyup rukun
yang sejati.
Menurut HK, sosok Romo Kir dapat dilihat dari sudut pandang marketing.
Pertama, dia punya komunitas loyal, yakni masyarakat Merapi. Kedua, ia
pastor yang tak dilambangkan sebagai sebuah salib saja, tapi sebagai
manusia berbudaya. Sehingga bisa merangkul semua pihak. Bahkan yang
saling bersengketa sekalipun.
Kemudian, secara blak-blakan, HK juga mengungkap akar masalah krisis
global dewasa ini. Yakni, pemasaran yang melulu berorientasi pada laba.
Seseorang sebenarnya belum mampu membeli suatu produk. Kendati
demikian, perbankan dan pengusaha menggunakan paham marketing "asal
untung". Akhirnya, konsumen terbuai membeli produk tersebut.
Tapi karena tak mampu membayar cicilan kredit, barang itu terpaksa
ditarik kembali. Ketika tak ada yang mampu membeli, terjadilah
penumpukan aset dan kolaps seperti sekarang. Dalam konteks ini, HK
melihat marketing religius, humanis, dan ramah lingkungan sebagai
solusi. Produk harus dekat dengan alam dan menjunjung nilai-nilai
ketuhanan. Sejatinya, Romo Kir dan komunitas budaya di lereng Merapi
telah menerapkan filosofi tersebut.
Lewat buku ini, Romo Kir juga mengungkap rahasia sukses gerakan budaya
di komunitasnya. Gunung Merapi selalu menggelontorkan energi dahsyat.
Sehingga ia mampu bertahan di tempat "panas" tersebut. Ia mengaku bukan
orang pintar dan tak punya gelar akademisi tertentu. Sumber
kreatifitasnya semata dari Merapi. Air, bebatuan, tanah, pasir, tanaman,
pepohonan, hutan, semuanya memancarkan kekuatan magis. Yang tak kalah
hebat ialah tradisi, kesenian, dan kebudayaan masyarakat di pelosok
kaki gunung Merapi.
Sedikit informasi ihwal Gubug Selo. “Gubug” tersebut berupa ruangan
besar dan terbuka. Uniknya, selain dipakai untuk perayaan Ekaristi,
dimanfaatkan pula untuk kegiatan yang berkaitan dengan seni dan budaya.
Menurur Lik Kir, bangunan ini melambangkan keinginan untuk terus
belajar. Jadi, merangkul semua, menghargai semua. Peraih Maarif Award
2010 ini melihat budaya Indonesia memang majemuk. Sehingga
spiritualitas komplementer lebih relevan. Kecenderungan resisten,
defensif, apalagi agresif perlu ditinggalkan. Praksis agama nan ramah
terhadap pluralitas kebudayaan niscaya menciptakan iklim yang lebih
sehat bagi kehidupan bersama (halaman 216).
Tak ada gading yang tak retak. Buku ini memiliki beberapa celah. Salah
satunya, terdapat beberapa kesalahan ketik. Sehingga sedikit mengganggu
kenyamanan membaca. Ke depannya, bila hendak dicetak ulang, peran
editor menjadi signifikan.
Terlepas dari kelemahan tersebut, antologi artikel ini niscaya
membuka wawasan sidang pembaca. Hingga kini kekayaan berlimpah dari
alam Merapi justru dijarah oleh para cukong dan kompradornya. Berkah
bumi Merapi belum dinikmati secara merata oleh masyarakat pedesaan.
Sepakat dengan pendapat Romo Kir, "Masa depan Merapi ada di tangan
mereka (baca: anak-anak lereng Merapi). Saya berharap mereka akan
menjadi penyelamat yang melayani makhluk lain sebagaimana Alam melayani
mereka." Selamat membaca! ***
Judul Buku : Tapak Romo Kir
Penulis : Kumpulan Tulisan Wartawan
Penerbit : Waktoe, Magelang
Cetakan : 1/Februari 2012,
Tebal Buku : xx + 273 halaman
Diresensi oleh T. Nugroho Angkasa S.Pd., Guru Bahasa Inggris di PKBM Angon (Sekolah Alam) Yogyakarta, pengelola http://www.angon.org/
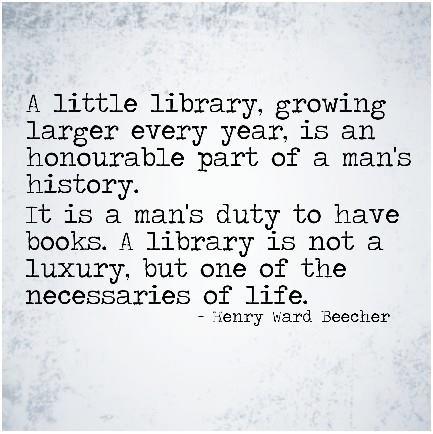


.jpg)



